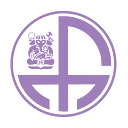Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023): Ketika Film Berbicara Pada Penontonnya
Ditulis oleh Fadhal (Kru’22)
“Gimana kalau kita bikin film hitam putih?”
Sebuah pernyataan kreatif yang terdengar sederhana dalam proses filmmaking, tetapi Yandy Laurens mampu membawanya pada pendekatan meta yang mengajak penontonnya untuk “ngobrol” melalui proses membuat film yang kita cintai.
Film meta merupakan gaya pembuatan film yang terang-terang menyatakan bahwa penontonnya sedang menonton karya fiksi. Film meta sering kali melanggar konvensi naratif dengan merujuk pada produksinya sendiri, seperti dengan menunjukkan peralatan produksi atau meminta karakter mendiskusikan pembuatan film.
Seperti yang dikemukakan Yandy dalam wawancaranya melalui IN-FRAME w/Ernest Prakasa, ide konsep film hitam putih lahir ketika ia menafsirkan ekspresi rasa duka ketika melihat sang ibu melihat bingkai-bingkai foto hitam putih mendiang sang ayah dan saudarinya. Proses pembuatan yang berjalan selama 8 tahun membuat film ini mengalami beberapa perubahan cara pandang: awalnya sekadar untuk mengetahui rasa duka sang ibu, kemudian beralih menjadi “jika ingin mengetahui rasa duka sang Ibu, ya ia lebih baik pulang bertemu ibu, ngobrol”. Konsep tentang duka dan ngobrol ini lah yang akhirnya menjadi tema besar Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023).
Ngobrolin Romance
Menarik ketika film hitam putih ini mengambil genre romansa yang bersanding dengan rasa duka. Ketika berdiskusi dengan teman tentang film ini, saya mendapati adanya kontra terhadap konsep ngobrol dalam film ini, beberapa berkata “masalah romansa nggak semudah itu untuk dingobrolin di dunia nyata.”
Karakter utama film ini, Bagus (Ringgo Agus Rahman) dan Hana (Nirina Zubir), pernah berdebat tentang bagaimana cara membuat film romansa antara insan paruh baya agar tetap bisa semanis film drama romansa remaja. Hana beranggapan bahwa romansa di usia mereka sudah tidak cocok untuk “cinta-cintaan” atau “jatuh cinta seperti di film-film”; masalah-masalah romansa di usia mereka dapat diselesaikan dengan cara ngobrol. Film ini sendiri berhasil membawa ngobrol menjadi plot device yang jenius menurut saya, sebagai cara untuk memberi tahu dan berkomentar ke penonton tentang banyak hal, terutama perkara romansa. Ya, bisa jadi benar “hubungan di dunia nyata gak semudah itu dan gak semua harus diomongin,” tetapi hal tersebut menjadi sesuatu yang film ini juga berusaha sampaikan.
Hubungan antar karakter dalam film ini memiliki cara komunikasinya masing-masing. Komunikasi antar Bagus–Pak Yoram merupakan bentuk komunikasi antara bawahan dan atasan. Bentuk komunikasi ke atas terjadi ketika Bagus menyampaikan ide ceritanya, serta bentuk komunikasi ke bawah ketika Pak Yoram berusaha mengontrol produksi dan sering menyelak ketika Bagus menyampaikan idenya. Proses ngobrol keduanya juga sering sedikit nakal dengan breaking the fourth wall (momen yang terjadi ketika seorang pemain memberi tanda kepada penonton atau kamera) melalui tatapan mata, atau secara tidak langsung ngobrol dengan penonton.
Kemudian, komunikasi antara Bagus–Hana terjadi secara horizontal karena status keduanya sama. Komunikasi Bagus–Hana selama film berlangsung, keduanya tak selalu semuanya diobrolin. Komunikasi antar keduanya mengalami perubahan — — renggang sejak sekuens 5 dan membaik ketika keduanya membuka kembali obrolan pada sekuens 7.
Ketiga, terdapat bentuk komunikasi pasangan Celine–Dion. Keduanya sering dicap sebagai bentuk komunikasi yang kurang sehat karena jarang ngobrol. Bentuk komunikasi keduanya selain sebagai bahan komedi, juga sebagai contoh gagal komunikasi ketika pasangan jarang ngobrol. Keduanya menjadi komentar tersendiri pada gagasan film ini, tetapi justru dibanding dengan hubungan Bagus–Hana, keduanya hadir dengan warnanya tersendiri dan bentuk komunikasi jarang ngobrol ini menjadi karakter tersendiri dalam sebuah hubungan romansa yang ternyata bisa jadi baik-baik saja.
Bentuk-bentuk komunikasi yang berbeda tersebut menjadi alasan mengapa film ini dirancang untuk meta. Hal ini merupakan cara bagi film ini untuk ngobrol ke penontonnya, bukan hanya mengenai benar atau salah cara komunikasi antar pasangan dengan cara diobrolin. Namun, melalui 8 sekuens pembabakan yang bukan hanya untuk menampilkan tentang produksi film atau sebagai 101 filmmaking, tetapi justru sebagai medium penyampai pesan dan caranya ngobrol bareng soal film, sulam alis, pekerjaan, pertemanan, romansa, juga khususnya cara kita memandang duka.
Tidak semua hal juga bisa diobrolin, atau malah menjadi mansplain (seorang pria menjelaskan sesuatu kepada seseorang dengan cara yang merendahkan, menggurui) seperti Bagus yang berusaha mengubah belief Hana melalui naskah yang ia tulis agar Hana move on dari dukanya dan menerima cintanya.
Memang, soal berdiskusi dan berdialog tak semudah di film ini, tetapi Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023) hadir dengan sangat indah seakan tanpa menggurui bagaimana etika kita memandang rasa orang lain, dalam artian, kita sebagai manusia didorong untuk “peka”, entah bagaimanapun caranya, mau buat film biar romantis, atau justru dengan dialog intim ngobrolin apa yang masing-masing dari kita perlukan.
Ngobrolin Etika Merekam Duka dalam Film
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023) membawa ke-meta-an dan topik perfilmannya justru menjadi subplot penggerak tentang pesan utamanya yang ingin diangkat, yakni duka.
“Terus kenapa film ini tentang film ya?”
Jika kita berkaca pada salah satu dialog tentang — mungkin — kebanyakan keyakinan pegiat film, bahwa melalui film kita dapat merasakan atau menjadi karakter dari film tersebut — dapat merasakan emosi hingga empati karakternya. Tapi, justru itu yang merupakan “false belief” kita. Karakter Hana yang diperankan oleh Nirina Zubir benar-benar efektif dalam menyampaikan hal tersebut, tentang Hana yang cerita hidupnya secara diam-diam ditulis dan akan difilmkan oleh orang lain (Bagus). Seringkali, pegiat film lupa akan etika dan perasaan karakter aslinya ketika ceritanya akan dikomersilkan dalam produk berupa film.
Belum lama ini rilis film Vina: Sebelum 7 Hari (2024) yang menarik perbincangan panas karena film tersebut dinilai eksploitatif dalam menayangkan kekerasan yang diambil dari kejadian nyata. Ada belief dari sang pembuat film bahwa produksi film tersebut ditujukan untuk edukasi dan membuka kasus kembali. Namun, pada sisi lain, film juga merupakan sebuah produk bisnis yang diperjual-belikan dengan adanya keuntungan finansial. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu dialog dalam film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023) ketika Hana mengetahui Bagus secara diam-diam menuliskan ceritanya untuk difilmkan.
Hana
“Lu kenapa sih Gus, kehabisan ide? Sampai manfaatin cerita hidup gw untuk kerjaan lo gitu.”
“Lu cuma cinta sama dunia film yang sempit dan kecil lu tuh! Yang lu anggap bisa ngubah dunia!
“Lu pikir dengan bikin film, lu bisa ngerasain apa yang orang lain rasain?”
Dari dialog tersebut, film ini secara langsung ngobrol ke kita bagaimana rasanya ketika hidup seseorang kita manfaatkan untuk kepentingan individualis. Atau bahkan kritik dan refleksi bagi kita penonton yang mengeluarkan waktu dan uangnya untuk menonton produk tersebut hanya demi pengalaman atas kepuasan sinematik.
Kembali lagi kepada “kenapa film?”, dari sini kita diperlihatkan juga bagaimana apabila hidupnya dimainkan oleh orang lain. Dalam film buatan Bagus, Hana diperankan kembali oleh Julie Estelle. Meta-akting oleh Julie sebagai Hana yang dari gerak-geriknya saja sudah berbeda membawa gambaran bahwa kehidupan seseorang tidak bisa serta-merta direka ulang dengan tujuan membawakan rasa yang sama. Bahwa “lewat film kita bisa merasakan orang lain” itu salah.
Apakah kita malah menjadi seperti Bagus yang merasa “dunia kecil sempit film dapat mengubah dunia”, padahal itulah false belief kita. Terutama sebagai penonton, salah satu hal yang menohok justru melalui komentar-komentar jenaka Pak Yoram (Alex Abbad) yang hadir komedik, tetapi sebetulnya menjadi refleksi bagi kita yang menyaksikan kehidupan pribadi orang lain yang sedang kita tonton. Contohnya, saat membahas adegan duka pada metafora peti mati, Pak Yoram meminta agar adegannya diperpanjang, ditambah soundtrack, dibuat lebih melodrama, “penonton minta diperas emosinya.” Balik lagi, terkadang kita lupa untuk merasakan menjadi karakter, bagaimana duka seseorang justru menjadi konsumsi hiburan. Bagaimana etika melihat kesedihan atau kemalangan orang lain.
Visi pengadeganan dan pengambilan sudut pandang ini haruslah dilihat dan mempertimbangkan sensitivitas juga etika dalam memotret duka atau kemalangan seseorang. Dalam hal membingkai adegan, tentunya memiliki keterbatasan berupa bingkai atau aspect ratio yang ditampilkan. Ketika ia memotret tentunya ada pengambilan keputusan untuk menampilkan objek dalam bingkai, serta mengabaikan hal lainnya untuk masuk dalam bingkai.
Hal ini mengingatkan saya tentang apa yang ditulis oleh Susan Sontag dalam “Regarding The Pain of Others”, soal etika menonton the pain of other sebagai sebuah produk yang berada pada garis tipis antara menarik empati dan simpati atau justru hanya menjadi sensasi belaka. Kebanyakan film apalagi film bergenre melodrama seringkali menjual produk duka sebagai sebuah sensasi dan nilai jual lebih, dan penonton seringkali luput atas etika menonton. Dari sini saja ke-meta-an dan topik perfilman Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023) hadir sebagai pengingat akan hal tersebut. Kita disadarkan dan menertawakan apa yang dilakukan Pak Yoram, dan apa yang kita perbuat adalah hal yang insensitif dan tidak etis.
Kembali pada belief bahwa melalui film kita dapat merasakan atau menjadi karakter dalam film tersebut, perlu diketahui bahwa sebagai pegiat film tentu harus menyadari bahwa kehidupan seseorang tidak bisa direka ulang dengan sama persis, atau bisa benar-benar mengerti perasaan karakter yang ditulis dalam naskah. Interpretasi penonton pada karakter juga pasti akan berbeda-beda.
Menyajikan rasa duka atau bahkan kekerasan perlu memperhatikan etika dan sensitivitas pembuatnya, juga kita (penonton) yang membayar untuk menonton. Film sendiri telah diatur dan diregulasi secara jelas bahwa ia merupakan barang dagang yang juga berisi nilai sosial, budaya, dan ilmu. Terdapat pula kode etik produksi film Indonesia yang menjaga produksi film sejak 1981. Dengan demikian, diperlukan kebijaksanaan dari kita pegiat film untuk menyadari adanya kepentingan bisnis dalam film dan etika-etika yang perlu diterapkan.
Ngobrolin dan Kritik Terhadap Industri Film Indonesia
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023) juga mendapat julukan sebagai “film yang mengkritik film”. Komentarnya pada industri film Indonesia menjadi gelak tawa miris bagi mereka yang mengikuti perkembangan film di tanah air ini.
Ada beberapa hal yang bisa diambil dari film ini mengenai proses produksi film di Indonesia. Banyak orang bilang bahwa industri film di Indonesia ini masih bayi jika dibandingkan, misalnya, dengan Hollywood. Bahkan sejak era Orde Baru dengan adanya aturan keprofesian pembuat film, rasanya jika diamati melalui film ini belum banyak berubah.
Salah satu yang diangkat adalah sosok sutradara rangkap pemain, sutradara, produser, investor yang menandakan kurangnya sumber daya manusia dalam keprofesian pembuatan film. Pak Yoram terutama, ia harus menunjuk Bagus yang berprofesi sebagai penulis naskah untuk menyutradarai sendiri filmnya setelah ditolak oleh Riri Riza dan Mira Lesmana.
Selain permasalahan profesi penyutradaraan, film ini juga menampilkan kerja kru-kru di balik layar yang jarang terapresiasi. Dari mulai susahnya re-roll adegan, menyiapkan take, sampai jam kerja yang tidak jelas. Keluhan dari pekerja film ditampilkan dengan sangat tepat dan jelas ketika tidak jelasnya jadwal jam shooting selesai atau bahkan entah sampai kapan mereka terlibat dalam produksi film. Permasalahan ini masih diperjuangkan oleh mereka para pekerja film untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik.
Belum lama terjadi kasus meninggalnya Rifqi Novara, seorang kru film, akibat kecelakaan setelah kelelahan kerja. Hal ini menjadi katalis bagi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) untuk merancang berdirinya Komite Pekerja Film sebagai wadah berserikat bagi pekerja film untuk memperbaiki ekosistem dan kondisi kerja industri perfilman, serta mendesak perbaikan kondisi kerja industri film.
Dan inilah mungkin obrolan terpenting Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang bukan hanya produk film meta romansa hitam putih, tetapi juga hadir secara luar biasa menjadi paket lengkap mulai dari obrolan soali romansa, komedi, refleksi terhadap proses produksi film, dan memahami rasa.
Referensi
Budiman, D. A. (2016). Perfilman Indonesia Harapan Dan Kenyataan. Perfilman Indonesia Harapan Dan Kenyataan, 15.
SINDIKASI, S. (2024, Agustus 30). Kecelakaan Pekerja Film, SINDIKASI: Perbaikan Kondisi Kerja Industri Film Semakin Mendesak. Retrieved from https://blog.sindikasi.org/kecelakaan-pekerja-film-sindikasi-perbaikan-kondisi-kerja-industri-film-semakin-mendesak/
Sontag, S. (2003). Regarding the Pain of Others. Penguin Books.
Roche, D. (2024). Meta in Film and Television Series. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Yandy Laurens, R. A. (2023, November 27). Nirina Zubir Ngamuk, Headphone Yandy Sampe Mau Meleduk‼️🤯😭 — IN-FRAME w/Ernest Prakasa. (E. Prakasa, Interviewer)