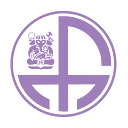Kukira Kau Rumah: Apa Cinta Bisa Setulus-tulusnya?
Sebelum membaca, disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena resensi ini mengandung spoiler.
Kukira Kau Rumah, film panjang pertama garapan sutradara Umay Shahab, nyatanya lain dari sekadar perhelatan cinta dua remaja: Niskala dengan ego tinggi dan Pram yang dengan lembut membawanya ke permukaan. Seolah setelah tirai panggung dibuka, terbuka lagi set selanjutnya yang lebih kelam, dua babak yang pada akhirnya memberi gambaran lebih luas.
Film ini dibuka dengan dua orang yang melalui segelintir peristiwa bersama dan kemudian menemukan ketertarikan satu sama lain — polemik klise benci jadi cinta. Di tengah film, Niskala ternyata berubah. Perubahan sifat ini digambarkan secara tiba-tiba dan agak terlalu jelas melalui klimaks tantrum yang seolah-olah meneriakkan: “Aku bermasalah!”. Sewajarnya, semua orang mulai bertanya-tanya, sampai akhirnya dijawab dengan obat yang diberikan Ibu Niskala. Niskala mengidap Bipolar sejak lama. Spontan, persepsi kepadanya berubah, bukan hanya dari calon kekasihnya Pram tetapi juga kita para penonton. Pergeseran konflik ini mendadak menggiring pandangan terhadap hubungan antara keduanya yang tidak lagi ikatan cinta biasa, menjadi ketergantungan yang lebih dalam, entah karena ketidakyakinan Niskala akan segala kesanggupan Pram menerimanya atau karena Pram yang berusaha mencintai secara tulus.
Kukira Kau Rumah cukup bisa meyakinkan dalam menuturkan cinta yang muncul tiba-tiba lalu melekat — bahkan ketika ada ‘tantangan’. Karakter Pram yang menemukan presensi Niskala untuk disayang sepenuhnya tidak terlihat tak wajar, tapi sesuatu yang bisa dipahami. Penonton bisa merasa pergeseran perasaan Pram yang semakin dalam. Ini bukan cerita cinta yang klise lagi, cinta setulus-tulusnya (buta) entah karena apa, tetapi cinta yang dibumbui konflik hati Pram yang bergejolak. Sayangnya, sudut pandang Pram ini disampaikan dengan cukup tergesa-gesa. Fokus film cenderung pada permasalahan Niskala dan semua situasinya. Pram diposisikan sebagai orang luar yang berusaha menerima Niskala apa adanya, padahal keduanya saling membutuhkan — bahkan mungkin Pram lebih bergantung pada presensi Niskala. Ini juga yang menimbulkan banyak tanda tanya pada konklusi akhir dari film ini: Pram yang mengakhiri hidupnya.
Kegelisahan Pram tidak dituturkan sedikit demi sedikit dari awal film, melainkan hanya ditonjolkan sebagai konklusi yang impulsif dan terkesan dangkal di akhir. Padahal mungkin perkembangan masalah Pram yang memuncak pada adegan akhirnya bisa disampaikan kalau saja konflik tidak diberatkan sepenuhnya pada kondisi Niskala. Semua diakhiri dengan Pram, tapi film ini bercerita tentang Niskala dan gangguan mentalnya. Oleh karena itu, kesan yang diberikan seolah-olah segenap ketulusan yang dihaturkan hanya berupa bentuk cinta dan kasih yang sia-sia. Jika dilihat dari kacamata penonton yang sejak awal disuguhi persoalan Niskala, peristiwa di akhir adalah hal yang tidak cukup berdasar, ada karena ketulusan Pram yang melampaui batas wajar.
Masalah ini juga jadi menimbulkan secuil pertanyaan lain: seperti apa bentuk gangguan mental yang ingin didepiksikan oleh film Kukira Kau Rumah? Kegelisahan Pram yang justru jauh lebih kompleks dan gelap dikubur, sementara hanya ada gambaran tangisan, tantrum, atau reaksi yang gamblang Niskala. Padahal dua-duanya merupakan gejala yang masuk akal, tetapi sayang tidak digali dengan merata.
Sebenarnya ‘ketulusan’ Pram untuk mencintai Niskala kendati apapun yang dialaminya bisa dibuktikan dengan lebih baik, andai saja karakter Pram ditelusuri lebih dalam lagi. Meski begitu, film ini sudah cukup baik dalam mempertahankan gejolak kasih yang jujur tanpa pamrih melalui hubungan Pram dan Niskala. Sebagai film layar lebar dengan penonton segala rupa, Kukira Kau Rumah cukup bisa menyeimbangkan polemik cinta dan isu gangguan mental yang masih bisa ditelan banyak orang.
-written by Ninan (kru’20)-