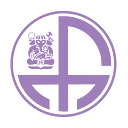Review: Fear Street (2021)
Film horor, romansa, remaja, dan (sedikit) komedi gagal.
Di era di mana film horor yang mengagetkan sudah menjadi seperti keseharian, Fear Street datang dengan konsep yang cukup “kekinian”.
Bukan horor biasa, tetapi lebih mirip petualangan dengan bumbu horor yang mengajak sedikit emosi penonton untuk terlibat di dalamnya. Ya, bagi saya, horor dalam film ini hanya salah satu bumbu, bukan hidangan utamanya. Lowkey, film ini sebenarnya hanya berkutat masalah romansa.
Hati-hati tulisan ini mengandung spoiler.
Fear Street Part One: 1994
Seri pertama dari trilogi ini bercerita secara linear: penonton diperkenalkan secara perlahan kepada dua kota ganjil yang bertolak belakang beserta karakter yang ada di dalamnya. Mulai dari drama antarwarga kedua kota, keanehan yang terjadi di dalamnya, sampai kutukan absurd-nya (untuk hal ini, akan saya jelaskan di bagian-bagian selanjutnya).
Pada seri pertama ini, penonton disuguhi dengan pertemanan insidental sekumpulan remaja akibat dihadapkan dengan kutukan atas nama penyihir bernama Sarah Fier. Akibat rasa sepenanggungan (setidaknya sampai dua pertiga film), hubungan antartokoh pun menjadi semakin intim. Dibumbui dengan drama-drama kecil di dalamnya, seperti cinta antara dua tokoh utama, yaitu Deena dan Sam. Lalu, cinta insidental, antara Kate dan Josh, akibat dorongan nafsu yang sarat akan “It’s the edge of our lives, we better enjoy the love that we shared while it lasts”. Sungguh terlalu klise dan kurang “ngena”.
Namun, sayangnya seperti yang digaungkan oleh trilogi ini, pada akhirnya penyihirlah yang tetap menang: pertemanan hancur berantakan dan pengorbanan cinta berakhir sia-sia (setidaknya untuk seri ini). Seri pertama, meninggalkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya Sarah Fier ini?
Fear Street Part Two: 1978
Seri kedua merupakan flashback dari kejadian yang berulang kali di-mention pada seri pertama. Awalnya, saya pikir kejadian ini hanyalah pelengkap semata. Namun, ternyata cukup memegang peranan sentral dalam keseluruhan cerita, yaitu mengungkap hampir setengah dari rahasia yang dicari di seri pertama, utamanya perihal Sarah Fier (meskipun menimbulkan kejanggalan apabila cukup memperhatikan).
Bagi saya, hubungan antartokoh pada seri kedua ini lebih “organik” dan depicting remaja pada masanya. Hubungan kakak dan adik antara dua tokoh utama yaitu Berman bersaudara, hubungan pertemanan insidental yang awalnya buruk antara Cindy Berman dan Alice, dan juga (lagi-lagi) hubungan cinta yang harus berakhir dengan pengorbanan.
Namun, pada seri kedua ini, tokoh utama (setidaknya yang penonton anggap sampai sebelum unnecessary plot twist dikeluarkan) lebih tersudutkan dengan masalah yang ada. Ibarat memakan buah simalakama, ia dihadapkan dengan situasi serbasalah: korbankan cinta atau saudara.
Mungkin, karena dari ketiga film yang ada, seri kedualah yang tidak hanya membawakan cinta sepasang kekasih saja. Core-nya adalah love-hate relationship antara kedua saudara. Hubungan antara Cindy dan Tommy hanyalah tambahan beban moral bagi Cindy, bukan isu utamanya. Begitupula hubungan Ziggy dan Nick yang hanya menjadi pemanis.
Fear Street Part Three: 1666
Meskipun sudah digaungkan dari seri pertama, baru pada seri ketiga inilah feel akan sihir terasa. Dengan latar zaman pertengahan, horor yang disajikan terasa lebih identik dengan supernatural. Namun, sayangnya, menurut saya seri ini hampir tidak ada bedanya dengan seri pertama, bedanya hanya di pengemasan dan jalan yang diambil tokoh utama saja.
Lagi dan lagi, film ini masih bercerita tentang cinta, tetapi dengan bumbu “terlarang” karena masih dianggap tabu pada masanya. Juga, yang membedakannya adalah adanya rahasia yang terungkap sepenuhnya. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, apabila cukup memperhatikan, ada yang janggal dari seri sebelumnya: Sarah Fier terlihat seperti bukan penyebab dari semuanya. Hal itu yang membuat plot twist pada seri ini kurang berasa karena sudah dapat ditebak sebelumnya.
Pengorbanan Sarah Fier pun bagi saya terlalu klise. Dibandingkan pengorbanan pada dua seri sebelumnya, kali ini terlalu tidak diperlukan dan terlalu cheesy, apalagi dengan menjadikan “cinta terlarang” sebagai bahan bakar utamanya. Hal ini akan saya bahas sedikit lebih dalam pada bagian selanjutnya.
Selepas dari cerita zaman pertengahan, film ini langsung banting setir menjadi film bacok-bacokan dengan balutan komedi. Pertemanan insidental dengan gap umur begitu jauh yang menurut saya cukup dipaksakan, guyonan tidak lucu yang dikeluarkan di tengah situasi menegangkan, alur yang diburu-buru, dan hal-hal lain yang menyebabkan bulu kuduk tidak lagi berdiri. Semuanya bercampur dan menjadikan seri ketiga ini (setidaknya bagi saya) sebagai seri yang paling tidak berarti dan setengah-setengah dalam hal eksekusi.
Korbankan cinta atau kau tidak akan baik-baik saja.
Sebenarnya, konflik pada trilogi ini sudah digambarkan secara utuh pada klip paling pertama: korbankan cinta atau kau tidak akan baik-baik saja. Trilogi ini mencoba untuk memainkan emosi, utamanya dalam hal pengorbanan cinta. Namun, sayang caranya klise dan kurang “ngena”. Pendapat pribadi, hanya seri kedualah yang cukup “masuk akal” dan dapat “ditolerir”: cinta antara sepasang kekasih yang apabila tidak dikorbankan dapat menyebabkan cinta sedarah terlenyapkan.
Apalagi, dua dari tiga film ini membawa isu LGBT yang sudah jadi santapan sehari-hari di dunia Hollywood. Hal tersebut memang tabu pada masanya, tetapi usaha meromantisasinya menjadi inti dari seri pertama dan seri ketiga terlalu “maksa”. Bagi saya, paling menjijikkan adalah victim framing ketika hubungan ini di-kambing-hitam-kan oleh warga Union sebagai penyebab kutukan yang didapat. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, pengorbanan atas cinta ini pun terlalu cheesy sehingga seri ini terlihat seperti tidak serius dalam mengeksekusinya. Bukannya saya anti-LGBT, tetapi terlihat jelas dipaksakan sehingga seperti setengah hati.
Lalu, formula yang cukup diulang-ulang, yaitu pertemanan insidental akibat dihadapkan kutukan, cukup membosankan. Hasilnya, ada kegagalan pada sepertiga seri ketiga. Dalam sekejap, pertemanan antartokoh yang berbeda umur cukup jauh dan berbeda latar belakang, terbentuk begitu saja. Asumsikan Ziggy berusia sekurang-kurangnya usia SMA pada seri kedua, berarti pada tahun 90-an, ia sudah berumur setidaknya 30 tahun. Namun, dengan mudahnya, ia bisa berteman begitu saja tanpa ada rasa respect yang begitu berarti dari Deena ataupun Josh, entah karena kekanak-kanakannya Ziggy atau karena apa. Bahkan, menurut saya, pandangan dari Deena dan Josh bahwa Ziggy lebih dewasa saja nyaris tidak ada.
Belum lagi, kritik saya terhadap Nick, si antagonis, yang kurang dalam hal motivasi. Apa motif tertentu yang ia miliki? Apa yang mendorongnya untuk melanjutkan tradisi? Apa alasan akar dari greed yang mengalir deras pada garis keturunannya? Sedikit tertawa karena pada dasarnya trilogi ini seperti hanya bercerita tentang pesugihan dengan bumbu tentara supernatural dan mendorong adanya pengorbanan cinta. Ya, lagi-lagi tentang cinta.
Dari sisi pensuasanaan dan artistik, saya suka bagaimana film ini memakai warna yang kontras dan saturasi cukup tinggi. Nuansa warna-warni cukup membuat film ini tidak kaku. Opini pribadi, inilah hal pertama yang membuat saya memiliki impresi bahwa ini bukan film horor, melainkan film petualangan. Saya, yang biasanya takut dan enggan menonton film horor, menjadi terdorong untuk menonton trilogi ini sampai habis.
Sinematografi dari film ini juga terbilang tidak seperti film horor pada umumnya. Mementingkan estetika, tetapi masih dapat menimbulkan kesan menakutkan dengan penempatan objek ataupun efek praktikal yang cukup bagus. Dari pemilihan busana, tone warna tiap serinya, lagu yang diputarkan, sampai pengambilan gambar yang tidak statis, semuanya nyaman untuk dirasakan dan dinikmati.
Namun, ada titik pada seri pertama di mana saya merasa tidak akan ada bedanya apabila seri ini berlatar tahun 1990-an ataupun masa sekarang, terutama karena efek artifisial yang terlalu berlebihan untuk masanya. Alih-alih menghidupkan suasana, malah membuat saya tidak takut dan tidak jijik lagi. Yaitu pada scene pada seri pertama di mana para “tentara supernatural” diledakkan dalam suatu ruangan, lalu berakhir dengan slime yang menyatu kembali. Seketika, unsur horor dari film ini lenyap begitu saja karena muncul rasa bahwa ini hanya kutukan ala-ala.
Konklusi dari saya, film ini dasarnya bukan horor, melainkan romansa. Cinta memiliki peran integral di dalam film ini, mungkin bisa dibilang jiwa dari cerita. Horor hanya berfungsi sebagai bumbu pada setiap petualangannya. Hasilnya? Cukup menegangkan hanya pada dua pertiga trilogi. Ya, sepertiga sisanya hanya bacok-bacokan berbalut komedi dan kisah cinta yang inautentik.
-written by Dasa (kru’20)-