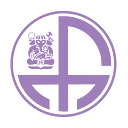Women From Rote Island (2023): Tentang Citra atas Eksotisme Alam dan Perempuan Rote yang Malang
Ditulis Fadhal (Kru’22)
Isu-isu mengenai keperempuanan belakangan ini menjadi perhatian yang cukup besar, khususnya mengenai kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Jika berkaca pada Festival Film Indonesia (FFI) beberapa tahun ke belakang, film yang hadir sebagai pemenang cerita panjang terbaik adalah film-film tentang perempuan. Lihat saja Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2018), Perempuan Tanah Jahanam (2020), Penyalin Cahaya (2021), Before Now, & Then/Nana (2022) — yang mana tema FFI tahun tersebut juga tentang perempuan — dan terakhir 2023, Women From Rote Island menyabet gelar yang sama.
Selain sebagai pemenang cerita panjang terbaik, Women From Rote Island juga berhasil memenangkan skenario asli terbaik, sutradara terbaik, dan pengarah sinematografi terbaik dalam FFI 2023 yang bertemakan Citra. Tiga hal teknis yang penting dalam sebuah film berhasil dimenangkan. Namun, kembali pada tema FFI 2023 tentang “Citra”, memunculkan beberapa pertanyaan serta kritik pribadi terhadap justifikasi kemenangan film dengan judul alternatif Perempuan Berkelamin Darah ini.
Citra, jika itu yang dilihat dalam Women From Rote Island, maka citra seperti apa yang ditampilkannya? Hal-hal yang ditampilkan dalam filmnya menuai beberapa reaksi yang sangat bertolak belakang. Ada yang merasa bahwa film ini terlalu nyata, mentah, dan kengerian yang ditampilkannya adalah suatu bentuk kejujuran. Namun, beberapa lainnya menilai hal ini hanyalah rentetan adegan kekerasan yang insensitif.
Kritik pertama yang sering dijumpai adalah absennya peringatan tentang adegan kekerasan yang merupakan hal krusial dan bagi sebagian orang dapat memicu hal traumatis hingga pengalaman tidak mengenakkan. Pengamatan saya pada kursi bioskop juga berkata demikian, ketika beberapa penonton perempuan merasa tidak nyaman selama menonton film tersebut.
Adegan kekerasan bertubi-tubi tanpa henti bagi sebagian orang adalah hal yang sangat tidak mengenakkan. Namun, timbul beberapa pertanyaan, apakah hal tersebut memang gambaran akan kondisi nyata di daerah tersebut? Jika kekerasan yang ditampilkan adalah realitas dan pendekatan Jeremias sebagai sutradara adalah mencoba memberikan hal yang sejujur-jujurnya, serealis, dan seotentik mungkin, serta kekerasan yang ditampilkan bukanlah hanya kekerasan “hip nan stylist”. Bagi saya, perlu adanya visi sang sutradara dan penulis serta penempatan sudut pandangnya dalam menciptakan pengadeganan.
Visi pengadeganan dan pengambilan sudut pandang ini haruslah dilihat dan mempertimbangkan sensitivitas, terlebih menyangkut kemalangan seseorang, bahkan komunitas. Menyebut apa yang ditampilkan Jeremias adalah citra yang realis, tetapi apa yang sebenarnya sebuah tontonan, memotret hal realis? Dalam hal memotret, tentunya sang pemotret memiliki keterbatasan berupa bingkai atau aspect ratio yang ditampilkan. Ketika ia memotret tentunya ada pengambilan keputusan untuk menampilkan objek dalam bingkai, serta mengabaikan hal lainnya untuk masuk dalam bingkai. Bagaimana dengan tontonan mengenai kekerasan? Jika kita menyaksikan laporan-laporan kekerasan, genosida di Palestina misalnya, seringkali kita ditampilkan gambar-gambar yang tak mengenakkan dan mengerikan dengan tujuan menyampaikan realita yang sesungguhnya. Dalam kasus lain, dokumenter Jagal (2012) melakukan reka adegan kekerasan untuk menyampaikan sejarah genosida 1965. Lalu bagaimana dengan penyampaian kekerasan dalam Women From Rote Island yang merupakan tontonan fiksi?
Kembali lagi pada pro/kontra terhadap visi Jeremias. Tentu penyampaian tentang realita ini sangat penting. Beberapa adegan bagi saya sudah cukup dalam menyampaikan realita di sana, bahkan tanpa perlu menampilkan adegan pemerkosaan. Namun, kritik dari saya adalah ketika momen kekerasan terlalu repetitif diulang-ulang berkali-kali khususnya pada Martha dan Bertha yang pada akhirnya hanya menghadirkan shock value dan menjadikan Martha sebagai samsak tinju lelaki. Begitu pula ketika film ini sendiri secara timeline berjalan mengikuti kekerasan yang dialami Martha, juga dalam urutan sekuens pembabakan ia mengalami kekerasan-black screen-muncul hitungan hari hingga bulan-Martha dan Bertha mengalami kemalangan. Hal ini bagi saya adalah hal yang insensitif dan mengabaikan pendekatan humanis pada sang karakter.
Sebuah produk tontonan yang menampilkan kekerasan berada pada garis tipis antara menarik empati dan simpati atau justru hanya menjadi sensasi belaka, tetapi perlu diingat film ini juga merupakan tontonan yang dikomersilkan. Women From Rote Island sesuai judulnya menampilkan keindahan eksotisme alam pulau Rote yang luar biasa, tetapi isi dibalik kosmetik estetika tersebut menyembunyikan kegelapannya. Pengadeganan oleh pengarah sinematografi, Joseph Fofid, dalam beberapa kesempatan berhasil memberikan gambar-gambar picturesque dan permainan kamera yang cantik, tetapi ada beberapa hal yang mengganjal secara teknis sinematografi. Jeremias sang sutradara memang terkenal dengan teatrikalnya, dengan ini ia menciptakan banyak adegan-adegan long shot yang menampilkan performa akting luar biasa oleh jajaran pemainnya, tetapi sayangnya beberapa pengadeganan panjang ini sedikit melelahkan dan sibuk sendiri pada pergerakan kamera. Selain itu, kritik secara pengarahan sinematografi adalah beberapa pemilihan pengadeganan yang tampak dilihat dari male gaze. Adegan transisi yang menyoroti bagian rok dan dada perempuan misalnya, dan juga adegan Martha melahirkan yang diambil pada sudut bawah sejajar dengan keluarnya bayi yang seakan ingin mempertegas judul Perempuan Berkelamin Darah.
Women From Rote Island tak ubahnya seperti produk women written by man lainnya. Dengan artian beberapa penulis pria ketika menulis cerita tentang perempuan kebanyakan atau bahkan di luar kesadarannya menuliskannya sebagai karakter sebagai objek untuk dilihat, bernasib malang dan seringkali mengalami kekerasan, pasif, penggambaran erotis, pelampiasan nafsu, serta memperkuat pandangan patriarkis. Dalam kata lain, hal-hal tersebut merupakan perspektif atas konsep feminisme dan psikoanalitik dalam film oleh Laura Murvey dalam esainya “Visual Pleasure and Narrative Cinema” tentang apa yang disebut dengan “male gaze”. Pendekatan male gaze ini dapat ditemui pada skenario film ini yang ditulis oleh sang sutradara Jeremias. Hal yang saya perhatikan pertama kali adalah ketika judul alternatif film ini Perempuan Berkelamin Darah yang memiliki konotasi pada peristiwa melahirkan. Dialog mengenai konotasi tersebut pun tak ubahnya menempatkan posisi pria dalam sosial, misalnya “laki-laki yang terlahir dari kelamin yang berdarah tidak akan berbuat seperti itu (negatif)”. Dialog yang seakan bernuansakan feminisme, tetapi tak ubahnya masih memiliki nilai-nilai phallocentrism (menempatkan nilai pria sebagai acuan sosial) dan terus mengaitkan perempuan dengan penderitaan. Begitu pula ketika saya mendiskusikan hal ini dengan teman perempuan, mereka sempat mempertanyakan mengenai pemilihan judul alternatif berbahasa Indonesia tersebut, bahkan kesannya cenderung menjijikkan.
Meskipun membawa nama film tentang perempuan, film ini justru tak memberikan penghormatan dan kelayakan pada karakter utamanya, Martha. Sedari awal kemunculan Martha pada film ini, seakan telah diberi vonis gila, vonis yang tak jelas mengapa dan menomorduakan Martha sebagai manusia yang mereduksi pengalaman traumatisnya. Seakan fungsi dia hanya sebagai karakter yang sangat karikatural dan satu dimensional, jauh dari kata memanusiakan. Penulisan yang male gazing ini terus menerus menampilkan Martha sebagai objek karakter tak berdaya dan seakan adanya fetish erotik pada kekerasan yang tak penting. Bagaimana tidak, vonis “gila” Martha hanya membawanya pada pemasungan dan perantaian atas tubuhnya dalam ruangan yang sepi, dalam rumah penuh perempuan, dan tanpa penjagaan, seorang pria aneh justru bisa masuk bebas dan melakukan pemerkosaan. Martha sang karakter utama terus-menerus tersiksa tanpa melibatkan penyembuhan traumanya, penyelesaian pada masalahnya pun tak melibatkan humanisme pada dirinya, bahkan ia tak dilibatkan sama sekali dalam penghukuman sang pelaku. Selain Martha, Bertha sang adik juga tak mendapatkan kejelasan dan keadilan. Ketika plot dirinya hanya untuk menyaksikan bentuk pemikatan seksual homoerotik pada remaja laki-laki dibawah umur — yang stance-nya tidak jelas dan cenderung homofobik — Bertha justru menjadi tontonan torture porn yang menayangkan adegan pembunuhannya.
Dalam film ini pemerkosaan dan maskulinitas berjalan beriringan. Seperti yang dikemukakan Aurelia Gracia melalui Magdalene.co, film ini hadir sebagai “Homoerotik yang Homofobik”. Ezra sang pelaku pemerkosa Martha juga merupakan pelaku pemikatan seksual pada kasus homoerotik pada remaja laki-laki. Maskulinitas adalah hal yang rapuh bagi sosok pria, begitu pula ketika posisinya dalam masyarakat khususnya perihal orientasi seksualnya dianggap atipikal, selain itu maskulinitas juga berarti pada kuasa dan dominasi. Untuk memperoleh maskulinitasnya, Ezra mendominasi mereka yang lebih renta, ia memilih seorang remaja laki-laki sebagai objek penyalur hasrat seksualnya melalui iming-iming pulsa, dan juga Martha yang sedang gila. Pemerkosaan pada Martha oleh Ezra juga tak lain atas kerentanan maskulinitas dirinya, ia yang memiliki orientasi seksual pada sesama gender memiliki ketakutan atas orientasinya tersebut dan terdorong oleh norma untuk melakukan seksualitas yang salah demi menghindari stigma sosial, atau apa yang disebut oleh sosiolog Eric Anderson sebagai homohisteria dalam kelompok masyarakat heteronormatif. Ezra melakukan pemerkosaan pada Martha menjadi tameng heteroseksualitas dirinya sebagai seorang laki-laki normal seutuhnya. Hal ini justru memperkeruh pandangan homofobia, juga merugikan perempuan.
Women from Rote Island secara langsung atau tidak langsung sudah memiliki citra feminis juga mengenai patriarki di Pulau Rote. Beberapa pendapat yang saya baca melalui media daring tentang penggambaran patriarki di film ini cenderung positif, terlebih mengenai kejujurannya pada kondisi patriarki yang masih ekstrem khususnya wilayah Indonesia Timur. Adanya tuntutan-tuntutan adat pada kuatnya ikatan hukum keluarga menjadi poin utama ketertekanan perempuan dan film ini berhasil memberikan kritik atas kondisi adat dan patriarki di wilayahnya. Penyelesaian konflik yang bergantung pada kekeluargaan, terutama pada kasus aib pemerkosaan dalam lingkup keluarga menjadi eskalasi konflik yang meninggi. Ketika Habel, pelaku pemerkosa Martha bahkan membongkar kubur leluhurnya untuk meminta maaf dan menyerahkannya sebagai upah adat, film ini memberikan posisinya untuk tetap mencarikan keadilan dengan karakter Mama Orpa memilih untuk tetap membawa ke jalur hukum, walau Habel secara batiniah telah ia maafkan.
Film ini juga memberikan gambaran penekanan bagi perempuan setempat untuk tunduk pada adat, terlebih pada Mama Orpa yang harus diam di rumah menunggu jenazah mendiang suami dikuburkan. Ketika ia melanggarnya, yang didapat adalah makian karma atas pelecehan yang dialaminya ketika berbelanja di pasar. Selain itu, film ini juga memberikan tekanan dan tuntutan yang sama bagi perempuan pada bagian “Beta Gagal Menjadi Ibu”. Penekanan pada tuntutan peranan maternal ini menjadi diberatkan dan mendikte kesempurnaan perempuan, khususnya ketika Mama Orpa yang dianggap gagal menjaga Martha dan Bertha, serta belum lagi filmnya memang kurang memberikan pendekatan yang humanis pada mereka bertiga. Nilai ideal ditempatkan pada sosok ibu yang baik ketika telah memenuhi fungsi perempuan dalam sosial, sedangkan yang tidak, seperti ketika Mama Orpa melanggar adat, tak ada simpati padanya, justru cap karma dan ibu yang gagal. Tuntutan maternal ini juga tak ayal pada sistem struktural dan budaya yang patriarkis. Adanya budaya yang mengatur fungsi perempuan yang ideal, bahkan diatur dalam Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Nomor 2 yang menyebutkan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Sayangnya, film ini sendiri juga terjerumus untuk mendikte peranan perempuan yang ideal dengan memberikan konklusi empowerment yang seakan menyerukan cara yang ideal untuk menjadi berdaya adalah dengan protes beramai-ramai dengan polisi wanita yang menghadang dan seakan sekali lagi memberikan gambaran baik bagi tokoh pria dengan memunggungi pemrotes.
Film ini sendiri berusaha menampilkan hal-hal subtil mengenai kebebasan perempuan melalui penggunaan simbolisme burung. Martha yang berusaha menyelamatkan anak burung, dialog “orang Rote tidak memelihara burung dalam kurungan”, hingga bagian akhir film melalui adegan membebaskan burung yang pada akhirnya hanya sekadar visual tanpa makna karena tokoh manusianya saja tak diberikan hal empatik.
Lantas film cerita panjang terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2023 ini membawakan citra tentang apa? Apakah juri FFI kali ini kembali pada penilaian yang mengedepankan eksotisme dan nilai-nilai yang sangat ke-Indonesia-an? Lalu jika citra yang ingin ditunjukkan adalah kondisi patriarki dan perempuan, melihat jajaran nominasi yang ada, bukan hanya Women From Rote Island yang menyuarakan tentang suara perempuan. Rasanya citra yang saya dapatkan adalah lagi-lagi kemalangan perempuan dan eksotisme alam Indonesia menjadi komoditas tontonan eksotik, serta kurangnya sensitivitas yang ditampilkan mengingat film ini juga ditujukan untuk komersil. Namun, pendapat saya ini sendiri merupakan subjektivitas, seni juga merupakan perkara yang subjektif, tetapi penilaian dan pengalaman penonton dalam siklus rekognisi dan apresiasi juga tak dapat diabaikan. Saya harap ke depannya, film-film dalam nominasi FFI seharusnya sudah dapat ditonton dan dinilai oleh penonton terlebih dahulu, sehingga ketersetujuan atau ketidaksetujuan atas kemenangan suatu film dapat dipertanggungjawabkan pada penonton.
Referensi:
Anderson, Eric. (2011) The Rise and Fall of Western Homohysteria. Journal of Feminist Scholarship
Gracia, A. (2024, February 28). Disadur dari Mmagdalene.co: https://magdalene.co/story/review-women-from-rote-island/
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.
Murvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 6–18.
Sontag, S. (2003). Regarding the Pain of Others. Penguin Books.